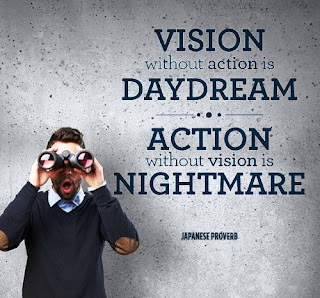Negara Republik Indonesia
telah memperoleh kemerdekaan melalui perjuangan gigih yang dilakukan oleh para
pahlawan. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mengisi kemerdekaan
ini dengan melaksanakan pembangunan disegala aspek kehidupan. Gerakan roda pembangunan yang dilakukan
membutuhkan tenaga kerja sebagai modal utama. Jumlah dan komposisi tenaga kerja
tersebut akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsung proses
demografi (kependudukan).
Tulis yang kamu cari
Halaman
Analytics
Adv
Fenomena Simlacrum
'Simulation is characterized by a precession of the model, of all models around the merest fact the model come first. Facts no longer have any trajectory of their own, they arise at the intersection of the models; a single fact may even be engendered by all the models at once. Simulation is no longer that of a territory, a referential being or a substance. It is the generation by models of a real without origin or reality; a hyperreal. The territory no longer precedes the map, nor survives it. Henceforth, it is the map that precedes the territory precession of simulacra it is the map that engenders the territory and if we were to revive the fable today, it would be the territory whose shreds are slowly rotting across the map. It is the real, and not the map, whose vestiges subsist here and there, in the deserts which are no longer those of the Empire, but our own. The desert of the real itself' (Baudrillard, 1983:32)
Jean Baudrillard dalam buku Simulations (1983) yang diterbitkan
dalam edisi bahasa Inggris mengintrodusir sebuah karakter khas kebudayaan
masyarakat barat dewasa ini. Menurutnya, kebudayaan barat dewasa ini adalah
sebuah representasi dari dunia simulasi, yakni dunia yang terbentuk dari
hubungan berbagai tanda dan kode secara acak, tanpa referensi relasional yang
jelas. Hubungan ini melibatkan tanda real
(fakta) yang tercipta melalui proses produksi, serta tanda semu (citra) yang
tercipta melalui proses reproduksi.
Dalam
kebudayaan simulasi, kedua tanda tersebut saling menumpuk dan terjalin untuk membentuk
satu kesatuan. Tidak lagi dikenali mana yang asli, yang real, dan mana yang
palsu atau yang semu. Semua menjadi bagian realitas yang dijalani dan dihidupi
masyarakat barat dewasa ini. Kesatuan inilah yang disebut Baudrillard sebagai simulacra atau simulacrum, sebuah dunia yang terbangun dari serangkaian nilai,
fakta, tanda, citra dan kode. Realitas tak lagi punya referensi, kecuali simulacra itu sendiri. Jadi, simulacra adalah ruang dimana mekanisme
simulasi berlangsung.
Simulacra
tidak memiliki acuan karena merupakan bagian duplikasi dari duplikasi, sehingga
perbedaan antara duplikasi dan yang asli menjadi kabur. Dalam ruang ini tidak
dapat lagi dikenali, mana hasil produksi dan mana hasil reproduksi, mana objek
dan mana subjek, atau mana penanda dan mana petanda.
Menurut
Baudrillard[1],
terdapat tiga tingkatan simulacra.
Pertama, simulacra yang berlangsung
semenjak era Renaisans hingga
permulaan Revolusi Industri. Simulacra
pada tingkatan ini merupakan representasi dari relasi alamiah berbagai unsur
kehidupan. Dalam tingkatan ini, realitas dunia dipahami berdasarkan prinsip
hukum alam, dengan ciri ketertiban, keselarasan, hierarki alamiah serta
bersifat transenden. Alam menjadi pendukung utama sekaligus determinan
kebudayaan. Tanda-tanda yang diproduksi dalam orde ini adalah tanda-tanda yang
mengutamakan integrasi antara fakta dan citra secara serasi dan seimbang. Hal
ini berkaitan erat dengan kehendak manusia zaman itu untuk mempertahankan
struktur dunia yang alamiah. Dengan demikian, prinsip dominan yang menjadi ciri
simulacra tingkat pertama adalah
prinsip representasi.
Kedua,
simulacra yang berlangsung seiring
dengan perkembangan era industrialisasi. Pada tingkatan ini, telah terjadi
pergeseran mekanisme representasi akibat dampak negatif industrialisasi. Objek
kini bukan lagi tiruan yang berjarak dari objek asli, melainkan sepenuhnya sama
persis seperti yang asli. Dengan kemajuan teknologi reproduksi mekanik, prinsip
komoditi dan produksi massa menjadi ciri dominan era simulacra tingkat kedua.
Ketiga,
simulacra yang lahir sebagai
konsekuensi berkembangnya ilmu dan teknologi informasi. Simulacra pada tingkatan ini merupakan wujud tanda, citra dan kode
budaya yang tidak lagi merujuk pada representasi. Selanjutnya dalam mekanisme
simulasi, manusia dijebak dalam ruang realitas yang dianggap nyata, padahal
sesungguhnya semu dan penuh rekayasa. Dengan contoh yang gampang Baudrillard
menggambarkan dunia simulasi dengan analogi peta. Menurutnya, bila dalam ruang
nyata, sebuah peta merupakan representasi dari suatu wilayah, dalam mekanisme
simulasi yang terjadi adalah sebaliknya. Peta mendahului wilayah.
Realitas
sosial, budaya, bahkan politik, dibangun berlandaskan model-model yang telah
dibuat sebelumnya. Dalam dunia simulasi, bukan realitas yang menjadi cermin
kenyataan, melainkan model-model[2].
Boneka Barbie, tokoh Rambo, selebritis syahrini, film india, telenovela, iklan
televisi, Doraemon atau Mickey Mouse adalah model-model acuan nilai dan makna
sosial budaya masyarakat dewasa ini. Inilah era yang disebut Baudrillard sebagai
era simulasi.
Sebagai contoh, wacana simulasi yang menjadi ruang pengetahuan telah dikonstruksikan oleh iklan televisi, di mana manusia mendiami suatu ruang realitas, di mana perbedaan antara yang nyata dan fantasi, atau yang benar dengan yang palsu, menjadi sangat tipis. Manusia hidup dalam dunia maya dan khayal. Media lebih nyata dari pengetahuan sejarah dan etika, namun sama-sama membentuk sikap manusia.
Dalam
era simulasi ini, realitas tak lagi memiliki eksistensi. Realitas telah melebur
menjadi satu dengan tanda, citra dan model-model reproduksi. Tidak mungkin lagi
kita menemukan referensi yang real, membuat pembedaan antara representasi dan
realitas, citra dan kenyataan, tanda dan ide, serta yang semu dan yang nyata. Semua
yang terlihat hanyalah campur aduk diantara semuanya.
Dalam realitas simulasi seperti ini,
manusia tak lebih sebagai sekumpulan massa mayoritas yang diam, yang menerima
segala apa yang diberikan padanya. Dalam bukunya In The Shadow of the Silent Majorities (1982), Baudrillard
menganalogikan kumpulan massa yang diam ini sebagai lubang hitam, black hole, dimana berbagai hal
informasi, sejarah, kebenaran, nilai moral, nilai agama terserap ke dalamnya
tanpa meninggalkan bekas apapun juga.
Kenyataannya, sifat simulasi dalam
media televisi telah mampu menyuntikkan makna yang seolah-olah ada pada
kehidupan nyata, meskipun sebenarnya hanyalah sebuah fantasi atau realisme semu.
Film, berita, telenovela, video clip,
iklan, tayangan olahraga, talk show
ataupun tayangan kesenian tradisional ditonton sebagai tontonan yang semata
untuk dinikmati tanpa harus bersusah payah berpikir kritis.
Dalam ruang semu
televisi, penonton seolah didaulat sebagai subjek otonom yang dapat memilih
atau menyeleksi suguhan apa yang akan ditontonnya. Mereka dapat memindahkan dan
menciptakan realitas dari tayangan yang satu ke tayangan lain tanpa adanya
referensi tunggal yang saling berkaitan. Dari berita politik tentang kenaikan
BBM, ke sinetron-sinetron bernuansa Bollywood,
lalu berpindah lagi ke film drama Inggris yang bersetting abad ke-18 M,
kemudian menonton kembali tayangan video
clip Katy Perry, lalu kembali menyaksikan berita gempa bumi di Nepal dan
seterusnya. Ruang dan waktu seolah terlipat dalam sebuah kotak kaca yang
bernama televisi. Sifat fragmentasi dalam dunia semu televisi inilah dunia yang
terpotong-potong, durasi pendek atau panjang, berubah dan berpindah yang
menjadikan para penontonnya terbuai oleh mitos tentang subjek yang otonom.
Padahal, menurut Baudrillard, semua ini hanyalah mistifikasi yang dijejalkan
ideologi kapitalisme demi produksi dan konsumsi. Kebenaran yang sesungguhnya,
bahwa pilihan dan otonomi penonton televisi sebenarnya tak lebih dari pilihan
semu. Otonomi yang dibatasi dan diatur oleh pilihan yang sudah ada[3].
Penonton, dalam wacana televisi, tak lebih dari objek mengalirnya berbagai
fakta, citra, impian dan fantasi, tanpa memiliki jati diri yang hakiki, sebuah
terminal dari berbagai jaringan tanda-tanda.
Dalam wacana televisi, penonton
dengan demikian tak lebih dari sekumpulan mayoritas yang diam[4].
Itulah mengapa tayangan siaran langsung sepakbola tetap ditunggu dan ditonton
meskipun harus menunggu hingga tengah malam. Menurut Baudrillard, hal ini
karena televisi sama sekali tidak berpretensi menawarkan makna luhur atau
transenden, kecuali ecstasy dan
kedangkalan ritual.
Kebudayaan
industri di atas menyamarkan jarak antara fakta dan informasi, antara informasi
dan entertainment, antara entertainment dan ekses-ekses politik. Masyarakat
tidak sadar akan pengaruh simulasi dan tanda (signs/simulacra). Hal ini membuat kita kerap kali berani dan ingin
mencoba hal yang baru yang ditawarkan oleh keadaan simulasi (membeli, memilih,
bekerja dan sebagainya). Teori ekonomi Marx, yang mengandung “nilai guna”
digunakan oleh Baudrillard dalam menelaah teori produksi dan didasarkan pada
semiotik yang menekankan pada “nilai tanda”. Jean Baudrillard membantah bahwa
kebudayaan postmodern kita adalah dunia tanda-tanda yang membuat hal yang
fundamental – mengacu pada kenyataan – menjadi kabur atau tidak jelas.
Dalam bukunya Symbolic Exchange and Death (1976) Baudrillard menyatakan bahwa
sejalan dengan perubahan struktur masyarakat simulasi, telah terjadi pergeseran
nilai-tanda dalam masyarakat kontemporer dewasa ini yakni dari nilai guna dan
nilai tukar ke nilai tanda dan nilai simbol. Ia menyatakan bahwa dalam
masyarakat konsumeristik dewasa ini, nilai guna dan nilai tukar, seperti
disarankan Marx, sudah tidak lagi bisa diyakini.
Kini, menurut Baudrillard, adalah
era kejayaan nilai tanda dan nilai simbol yang ditopang oleh meledaknya citra
dan makna oleh media massa dan perkembangan teknologi. Jika dikaitkan dengan
pernyataan Marx, terdapat dua nilai tanda dalam sejarah kebudayaan manusia
yakni, nilai guna (use value) dan
nilai tukar (exchange value). Nilai
guna merupakan nilai asli yang secara alamiah terdapat dalam setiap objek.
Berdasarkan manfaatnya, setiap objek dipandang memiliki guna bagi kepentingan
manusia. Inilah nilai yang mendasari bangunan kebudayaan masyarakat awal.
Selanjutnya dengan perkembangan kapitalisme, lahir nilai baru yakni nilai
tukar. Nilai tukar dalam masyarakat kapitalis memiliki kedudukan penting karena
dari sanalah lahir konsep komoditi. Dengan konsep komoditi, segala sesuatu dinilai
berdasarkan nilai tukarnya.
Dalam wacana simulasi, manusia
mendiami ruang realitas, dimana perbedaan antara yang nyata dan fantasi, yang
asli dan palsu sangat tipis. Dunia-dunia buatan semacam Disneyland, Universal Studio,
China Town, Las Vegas atau Beverlly Hills,
yang menjadi model realitas semu Amerika adalah representasi paling tepat untuk
menggambarkan keadaan ini. Lewat televisi, film dan iklan, dunia simulasi
tampil sempurna. Inilah ruang yang tak lagi peduli dengan kategori-kategori
nyata, semu, benar, salah, referensi, representasi, fakta, citra, produksi atau
reproduksi semuanya lebur menjadi satu dalam keterkaitan tanda[5].
Simulasi akan menciptakan suatu
kode, yaitu cara pengkombinasian tanda yang disepakati secara sosial, untuk
memungkinkan satu pesan dapat disampaikan dari seseorang kepada orang yang lain[6].
Dalam dunia simulasi, identitas seseorang tidak lagi ditentukan oleh dan dari
dalam dirinya sendiri. Identitas kini lebih ditentukan oleh konstruksi tanda,
citra dan kode yang membentuk cermin bagaimana seorang individu memahami diri
mereka dan hubungannya dengan orang lain. Lebih lanjut, realitas-realitas
ekonomi, politik, sosial dan budaya diatur oleh logika simulasi ini, dimana
kode dan model-model menentukan bagaimana seseorang harus bertindak dan
memahami lingkungannya.
Saat ini, hampir seluruh dimensi
kehidupan masyarakat timur telah dipengaruhi oleh masyarakat barat yang dituntun oleh logika ekonomi kapitalis yang
menawarkan keterbukaan, kebaruan, perubahan dan percepatan konstan. Dalam
keadaan demikian, persoalan gaya hidup, mode dan penampilan menjadi nilai baru
yang menggantikan nilai kebijaksanaan, kearifan dan kesederhanaan. Konsep
Baudrillard mengenai simulasi adalah tentang penciptaan kenyataan melalui model
konseptual atau sesuatu yang berhubungan dengan “mitos” yang tidak dapat
dilihat kebenarannya dalam kenyataan. Model ini menjadi faktor penentu
pandangan kita tentang kenyataan. Segala yang dapat menarik minat manusia
seperti seni, rumah, kebutuhan rumah tangga dan lainnya ditayangkan melalui
berbagai media dengan model-model yang ideal, disinilah batas antara simulasi
dan kenyataan menjadi tercampur aduk sehingga menciptakan hyper reality dimana yang nyata dan yang tidak nyata menjadi tidak
jelas.
Ada Apa Dengan Cinta 2 ; Terjebak Nostalgia dalam Kisah Cinta yang Seperti Itu Saja
Kejutan besar dari
dunia perfilman Indonesia saat ini datang dari sebuah film berjudul Ada ApaDengan Cinta 2. Jarak ratusan purnama yang dinanti oleh jutaan mata tentang
kisah Cinta dan Rangga yang pernah menghias layar lebar hingga layar kaca kembali menggema.
Dulu, saat menonton film ini, Blogger Eksis masih berseragam putih biru dengan wajah nan lugu. Sekarang, saat menonton, saya juga berseragam kantor putih biru namun sudah mampu menyimak adegan demi adegan yang penuh haru dengan nuansa rindu.
Dulu, saat menonton film ini, Blogger Eksis masih berseragam putih biru dengan wajah nan lugu. Sekarang, saat menonton, saya juga berseragam kantor putih biru namun sudah mampu menyimak adegan demi adegan yang penuh haru dengan nuansa rindu.
Ketika Teknologi Tersinkronisasi di Kota Cirebon yang Memikat Hati
Di wilayah Jawa, khususnya provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan pengguna mobile data tertinggi di Indonesia. Selain Bandung, kota Cirebon mulai dikenal sebagai kota yang memiliki pertumbuhan industri kreatif yang maju secara signifikan sehingga membutuhkan koneksi internet cepat dan stabil untuk memenuhi kebutuhan penduduknya.
Tepat, pada bulan Agustus lalu, Smartfren secara resmi meluncurkan layanan 4G LTE. Smartfren telah melakukan test-drive di beberapa wilayah yang sudah dijangkau jaringan 4G LTE sekitar daerah Cirebon. Pihak Smartfren melakukan edukasi terhadap penduduk kota Cirebon agar Cirebon mampu membuktikan diri menjadi Smart City.
Nikmati Sensasi Belanja Online di Elevenia*
Hey,
bloggers…
Akhir-akhir ini, Blogger Eksis kena virus online shopping syndrome. Yah, karena kemudahan mengaksesnya, jadi tinggal browsing, klik sana sini sambil cari yang pas dihati, bayar dengan cara yang beragam dan langsung dateng deh ordernya seketika. Semua itu tanpa perlu mengeluarkan tenaga dan waktu yang sia-sia. Apalagi hidup di kota megapolitan kaya Jakarta, kadang kalo harus ke mall untuk shopping, kelamaan diperjalanan dibanding belanjanya. Iya kan?... Seharusnya Jakarta itu bukan kota megapolitan, tapi kota kemacetan.
Akhir-akhir ini, Blogger Eksis kena virus online shopping syndrome. Yah, karena kemudahan mengaksesnya, jadi tinggal browsing, klik sana sini sambil cari yang pas dihati, bayar dengan cara yang beragam dan langsung dateng deh ordernya seketika. Semua itu tanpa perlu mengeluarkan tenaga dan waktu yang sia-sia. Apalagi hidup di kota megapolitan kaya Jakarta, kadang kalo harus ke mall untuk shopping, kelamaan diperjalanan dibanding belanjanya. Iya kan?... Seharusnya Jakarta itu bukan kota megapolitan, tapi kota kemacetan.
Efektivitas Komunikasi
 |
| Tips cerdas berkomunikasi |
Hidup Tujuan Saya (HTS)
Dalam setiap diri setiap manusia, tentu manusia mempunyai berbagai macam tujuan. Ada tujuan yang bersifat Duniawi dan ada juga tujuan yang bersifat Ukhrowi atau Akhirat...
Berikut ini Blogger Eksis akan mengemukakan tujuan hidup setelah seperempat abad saya hidup di dunia ini. Dan bagian ini akan menjadi fragmen dari proses perjalanan hidup saya untuk membentuk suatu kisah hidup di episode-episode berikutnya . . .
Pertama, saya harus menjadi sarjana lulusan ilmu komunikasi. Bagi saya, Pendidikan ialah proses pengembangan diri. Suatu proses yang dapat membina nilai-nilai kehidupan menjadi unsur tata kelakuan yang terpuji. Ilmu yang telah saya pelajari, harus segera saya sebarkan ke masyarakat agar saya bisa menjadi sosok yang bermanfaat untuk orang lain dan menciptakan hablumminannas(hubungan antar sesama manusia). Bekal pendidikan yang saya peroleh juga akan menjadi pedoman untuk mewujudkan cita-cita saya.
"Pendidikan bukan persiapan untuk hidup
Pendidikan adalah hidup itu sendiri"
Trilogi 99 Cahaya di Langit Eropa ; Film Religi Kurang Esensi dan Sinergi
Film
adalah wahana untuk menyampaikan berbagai pesan kepada khalayak melalui sebuah
media cerita. Film juga merupakan medium ekspresi artistik sebagai suatu panca
indera bagi para seniman dan insan perfilman dalam rangka mengutarakan
gagasan-gagasan dan ide cerita. Mulai dari kisah cinta yang menggelora, kisah
cita-cita yang menggebu, dan kisah cipta yang menginspirasi. Semua telah
dihadirkan para sineas perfilman dengan rasa yang berbeda.
Berkembangnya dunia sinema Indonesia hingga tahun 2014 telah
menghasilkan berbagai genre
film. Selain sebagai hiburan
ternyata film mengandung
nilai atau pesan yang terkandung didalamnya sehingga memiliki banyak penikmat dan penggemarnya
masing-masing.
Beberapa
film di Indonesia yang menjadi karya dari sutradara-sutradara ternama juga
diangkat dari beberapa novel yang laris dipasaran atau menjadi best seller. Film-film tersebut mampu
eksis ditengah persaingan dunia industri perfilman nasional. Misalnya, Ketika
Cinta Bertasbih (Chaerul Umam), Laskar Pelangi (Mira Lesmana-Riri Riza), Sang
Pemimpi (Riri Riza), Edensor (Benni Setiawan), Negeri 5 Menara (Affandi Abdul
Rachman), 5 cm (Rizal Mantovani), Perahu Kertas (Hanung Bramantyo), Tenggelamnya
Kapal Van der Wijck (Sunil Soraya), dan Marmut Merah Jambu (Raditya Dika)
berhasil mencetak rekor penonton tertinggi.
Meski memiliki dimensi yang berbeda,
novel dan film saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Banyak film-film
berkualitas yang diadaptasi dari sebuah novel menjadi laris. Tak jarang, film
hasil adaptasi novel mendapatkan sambutan yang sama baik dengan novel yang
bersangkutan. Tak dapat dipungkiri sukses suatu novel merambat pula kepada
sukses suatu film untuk ditonton oleh masyarakat.
Salah
satu contoh film adaptasi novel paling laris ditahun 2014 adalah film berjudul
99 Cahaya di Langit Eropa. Film ini adalah sebuah film yang diangkat dari novel
yang ditulis oleh Hanum Salsabela Rais, putri tokoh nasional Amien Rais. Cerita
dalam novel tersebut ditulis bersama suaminya, Rangga Almahendra dan
diterjemahkan kembali ke dalam sebuah bentuk skenario oleh Alim Sudio. Kisah
ini berdasarkan pada pengalaman Hanum dan Rangga selama 3 tahun tinggal di
benua biru.
Sesungguhnya
novel dan film itu tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Alasannya, karena
masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Begitu juga yang
terungkap dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa. Jika kita lihat dari segi
kelengkapan cerita, sangat terlihat cerita yang ditampilkan dalam film tidak
selengkap yang telah tertulis dalam novelnya. Beberapa penjelasan-penjelasan
tentang sejarah Islam tidak mampu divisualisasikan secara detail dalam film
ini. Seharusnya hal-hal tersebut bisa menjadi tantangan tersendiri bagi sineas
perfilman Indonesia.
Meskipun
demikian, film 99 Cahaya di Langit Eropa bisa menjadi tontonan yang memuat
pesan toleransi yang sangat indah. Padahal, film-film Indonesia sudah sangat
jarang menampilkan film yang berisi dan memberikan pesan yang mengandung unsur
edukasi kepada masyarakat. Film 99 Cahaya di Langit Eropa berusaha membuat
energi baru dengan mengungkap pesan-pesan yang mendidik dan berdampak pada
publik terutama dalam segi religi yang saling mengasihi.
Tema film ini bercerita tentang pengalaman
sejarah dan peradaban umat manusia di negeri orang dalam mempertahankan
keyakinan, cinta, dan prinsip di tengah sekulerisme Eropa yang dibalut dengan
persahabatan dan pengungkapan misteri peradaban Islam. Unsur penciptaan karya
film bernuansa religius dibuat dengan konflik, penokohan, dan wadrobe yang pas. Namun, konflik
terkesan sederhana dan datar karena hanya berusaha menerjemahkan bahasa
kata-kata ke dalam sebuah visual yang membuat penonton harus menafsirkan
sendiri. Tidak ada dramaturgi yang terbentuk dalam film ini sehingga banyak
orang menilai bahwa film ini adalah sebuah film semi dokumenter atau film
sejarah Islam yang mencoba mengislamisasi diri.
Konflik
ketika kaum urban sulit mendapatkan pekerjaan di Eropa, konflik batin ketika sosok
Rangga harus memilih antara mengikuti ujian studi akhir atau melaksanakan
ibadah sholat Jum’at, dan konflik antara Hanum dan tetangganya yang terganggu
hanya karena bau ikan asin dan suara televisi yang berisik. Ketiga konflik
tersebut terkesan dipaksakan dalam setiap adegan sehingga terlihat janggal atau
aneh bahkan bisa menimbulkan makna ambigu. Seharusnya,
hal-hal yang mengungkapkan pertentangan atau konflik dalam sebuah film yang
menyangkut perbedaan pendapat dan nilai biasanya lebih disukai oleh penonton. Film
ini pun kehilangan esensinya.
Esensi sebuah film adalah rangkaian gambar (visual). Untuk
memahami makna yang terkandung di dalam gambar hasil rekaman (video) tidaklah
mudah. Kendatipun seseorang merasa mengerti tentang sesuatu yang terdapat di
dalam gambar, tetap saja ada hal-hal yang tidak bisa dipahami. Maka, sebuah
gambar menjadi sangat tergantung kepada siapa yang menginterpretasikan.
Penonton yang melihat gambar tertentu akan menginterpretasikan gambar tersebut
menurut pikirannya yang didasari oleh pengalaman hidupnya atau pola pikirnya
hingga mempunyai kesan tertentu.
Beberapa adegan dalam film juga
digambarkan dengan penggunaan dialog yang membuat penonton harus berpikir
dengan logika. Misalnya dialog dua orang asing yang menganggap roti croissant sebagai bentuk dari bendera
Turki yang jika dimakan sama saja dengan menghina muslim. Lalu, ada juga dialog
seorang dosen yang berusaha menafsirkan makna bismillah saat Rangga meminta
izin untuk mengubah waktu ujiannya yang bentrok dengan ibadahnya. Dialog dalam
dua adegan tersebut memang mengalir, namun penonton harus mampu mencerna kata
demi kata yang terucap oleh pelakunya karena visual adegan dibuat dengan potongan
gambar yang biasa saja, tanpa ada suspence
atau punching line.
Namun, Film 99 Cahaya di Langit
Eropa cukup berhasil sebagai film yang menyampaikan informasi mengenai
jejak-jejak agama Islam di benua Eropa. Film ini membawa
kita untuk memahami sejarah kejayaan Islam di tanah Eropa tanpa terkesan
menggurui. Melalui film ini kita menelusuri sejarah Islam di Eropa terutama
dari masa Dinasti Umayyah dan Ustmaniyyah. Kita mampu melihat jatuh bangun
peradaban Islam yang pernah menyinari daratan Eropa. Disamping itu, kita juga
dapat menyimak perjalanan Fatma Pasha. Sosok imigran dari Turki yang menjadi
sahabat Hanum untuk mencari kehidupan yang lebih baik sekaligus menyebarkan
cahaya Islam dan menghapus stereotipe negatif tentang Islam yang sudah
mengakar kuat di Eropa. Energi sejarah islam yang masih kurang dalam film ini
ialah tentang sosok Kara Mustafa Pasha yang hanya selintas diceritakan dan
membuat penonton terus bertanya-tanya siapakah sosok beliau yang mampu memberi
pengaruh dalam Islam.
Kita
harus mengakui bahwa menonton film ini lebih seperti melihat kembali
ensiklopedi kemegahan Eropa dan sejarah Islam dibandingkan dengan mengajak
penonton untuk turut serta merasakan apa yang para tokohnya rasakan. Logisnya, film
ini memang seperti dibuat dari sudut pandang sang penulis novelnya. Esensi
cerita pun justru menjadi bias dan kosong. Konflik-konflik dalam cerita berusaha
diungkap dan ditampilkan melalui sejumlah monolog yang dilakukan oleh tokoh
Hanum. Namun, penggarapannya terkesan kurang rapi karena cerita yang tersaji
tidak mampu mengikat emosi penonton.
Film yang
mengambil lokasi syuting di empat negara Eropa: Vienna (Austria), Paris
(Perancis), Cordoba (Spanyol), dan Istanbul (Turki) juga unggul dalam sisi sinematografi karena berhasil menampilkan unsur
visual panorama kota-kota tersebut menjadi magnet tersendiri bagi penonton. Ketajaman
gambar dan corak penggambarannya mampu menggugah penonton untuk mengunjungi
empat kota itu. Walaupun harus kita akui establish
shot yang ditampilkan tampak terlalu banyak. Entah untuk memperpanjang
durasi atau memang strategi pasar pemilik modal yang membiayai film ini
menjadikan sebuah lahan promosi pariwisata tersendiri.
Sisipan
adegan-adegan iklan juga sedikit mengganggu jalan cerita. Adegan dibuat demi
komersial semata seperti kebanyakan film-film Indonesia lainnya. Tidak tercipta
dalam suatu makna yang memiliki unsur drama. Untung saja, pihak sponsor yang terlibat
dalam produksi film ini tidak terlalu banyak sehingga masih terlihat sewajarnya
walaupun tidak tergarap secara memuaskan. Seperti adegan pengambilan uang di
ATM yang dilakukan oleh Rangga.
Unsur-unsur lain yang juga tampak mengganggu dalam film
ini ialah editing
subtitle dialog yang kurang rapi. Pada film ini juga tidak
diceritakan latar belakang beberapa karakter orang asing yang ternyata bisa
berbahasa Indonesia dengan fasih seperti Fatma Pasha dan Ayse dari Turki,
Marion Latimer dari Perancis, Khan dari Pakistan, serta Maarja dan Stefan.
Memang sulit memaksakan para aktor atau aktris untuk menguasai bahasa asing
sesuai perannya masing-masing, namun jika para sineas berhasil menggarapnya,
maka film ini akan berpeluang untuk dikenal lebih luas di mancanegara atau go international.
Pada
akhirnya, sinergi antar semua unsur yang tergabung dalam film ini memang
bertumpu pada cerita. Materi cerita novel 99 Cahaya di Langit Eropa memang
terlalu luas untuk dimuat dalam satu kisah visual. Namun, banyak penonton
beranggapan bahwa materi cerita tersebut memiliki nilai komersial yang tinggi
sehingga para produser memutuskan untuk produksi sekuel film 99 Cahaya di
Langit Eropa menjadi dua bagian. Ada 99 Cahaya di Langit Eropa Part 2 dan 99 Cahaya di Langit Eropa Final Edition. Kondisi demikian sudah
menjadi strategi marketing tersendiri para pemilik modal. Tetapi, penonton pun
banyak yang merasakan tidak mencapai klimaks untuk menonton film ini. Sinergi
film ini pun seakan sirna di sekuel-sekuel film berikutnya.
Jika
99 Cahaya di Langit Eropa terkesan berusaha untuk tampil dengan kisah
yang lebih luas tentang suatu perjalanan religi, maka 99 Cahaya di Langit
Eropa Part 2 jelas dapat dirasakan sebagai sebuah bagian
penceritaan yang lebih personal. Meskipun beberapa konflik yang dihadirkan
kurang mampu terasa esensial dan gagal bersinergi pada unsur sinematografi dari
sekuel film ini sebelumnya.
99
Cahaya di Langit Eropa Part 2 hanya memberi fokus yang lebih kuat pada kisah
kehidupan kedua peran utama dalam film ini, yaitu Hanum dan Rangga dalam sebuah
narasi. Penonton hanya disuguhkan dengan kualitas akting yang cukup meyakinkan
dari sisi teknikal serta penampilan para pemeran, 99 Cahaya di Langit Eropa
Part 2. Tidak begitu banyak yang bisa kita apresiasi untuk sekuel ini,
namun setidaknya sineas mulai melakukan perbaikan kualitas yang lebih layak
untuk suatu tontonan sebuah film.
Pada
akhirnya, menonton film 99 Cahaya di Langit Eropa akan membawa kita untuk merasakan
suatu cerita perjalanan spiritual yang telah dialami oleh Hanum dan suaminya.
Kita bisa merasakan bahwa kita masih jarang membuka mata untuk melihat dunia
dan segala isinya, terutama yang berkaitan dengan ajaran keagamaan. Perjalanan
yang terekam dalam film tersebut harus mampu membawa penonton untuk naik ke
derajat yang lebih tinggi dalam memperluas wawasan sekaligus memperdalam
keimanan. Meskipun, jenis film religi ini masih belum tampak esensi dan sinergi
yang memadai.
Langganan:
Komentar (Atom)